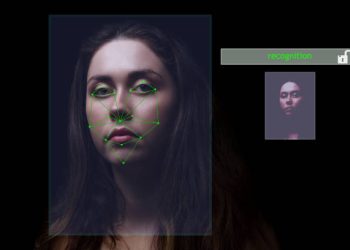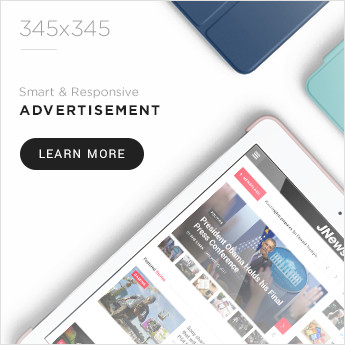Sejak awal sejarah filsafat, manusia selalu berusaha memahami posisi dirinya di dalam kosmos. Bagi Plato, semesta adalah cermin ide-ide yang sempurna; bagi Aristoteles, alam adalah tatanan teleologis di mana segala sesuatu bergerak menuju tujuan yang hakiki. Bahkan tradisi keagamaan, dari Kristen hingga Islam, menempatkan dunia sebagai ciptaan ilahi yang baik adanya. Keyakinan fundamental ini—bahwa semesta pada dasarnya baik atau setidaknya rasional—telah lama menopang kerangka etika, estetika, dan harapan manusia.
Namun sains modern, khususnya fisika termodinamika, justru menyingkap wajah lain dari realitas. Apa yang selama berabad-abad dianggap harmonis, ternyata tunduk pada hukum yang kejam: entropi.
Segala sesuatu, tanpa kecuali, bergerak menuju kehancuran, ketidakteraturan, dan kematian panas semesta. Tidak ada tujuan moral, tidak ada rancangan teleologis, tidak ada “kebaikan” yang melekat pada struktur kosmos. Yang ada hanyalah peluruhan energi yang tak dapat dihentikan.
Filsafat Yunani Kuno menganggap kosmos sebagai kosmos—sebuah keteraturan yang indah. Kata ini sendiri berarti “ornamen” atau “hiasan,” menandakan bahwa alam dipandang sebagai sesuatu yang bernilai intrinsik. Bahkan Stoa mengajarkan bahwa hidup baik adalah hidup sesuai dengan alam, karena alam diyakini rasional.
Tetapi penemuan hukum kedua termodinamika di abad ke-19 menghancurkan ilusi itu. Alih-alih keteraturan, realitas tunduk pada degradasi permanen. Bintang-bintang yang berkilau adalah api yang sedang sekarat. Tumbuhan yang hijau hanyalah mesin pembakar energi matahari. Tubuh manusia, dengan segala kecerdasannya, hanyalah susunan rapuh dari materi yang menuju kehancuran biologis.
Dari sudut pandang ini, alam bukanlah rumah yang ramah, melainkan mesin raksasa yang bekerja tanpa henti menghancurkan dirinya sendiri—dan semua yang ada di dalamnya.
Salah satu ilusi yang paling kuat adalah keyakinan bahwa kehidupan membantah hukum entropi. Kita menyaksikan organisme berkembang, berevolusi, membangun kompleksitas yang mengagumkan. Sejarah Bumi bahkan dipenuhi dengan kisah kebangkitan: setelah setiap kepunahan massal, kehidupan muncul kembali dengan bentuk yang lebih beragam.
Namun secara termodinamis, kehidupan bukanlah antitesis entropi, melainkan instrumen pengakselerasinya. Setiap metabolisme, setiap tarikan napas, setiap langkah evolusi bekerja dengan cara memecah energi tinggi menjadi energi rendah. Kehidupan tidak melawan kehancuran; ia mempercepatnya. Bahkan peradaban manusia, dengan teknologi dan industrinya, hanyalah puncak dari mekanisme yang mempercepat peluruhan energi planet.
Kreativitas biologis, dengan demikian, hanyalah topeng estetis dari kerja mesin kosmik yang buta.
Krisis Etika: Apa Arti Kebaikan di Alam yang Bermusuhan?
Jika realitas adalah destruktif pada hakikatnya, maka seluruh kerangka etika klasik runtuh. Bagaimana mungkin kita berbicara tentang “hidup baik” bila hidup sendiri hanyalah bentuk keterlibatan dalam mesin kehancuran? Apakah “berbuat baik” berarti mengikuti alam—padahal alam sendiri sedang menghancurkan segala sesuatu?
Di sinilah kita menemukan paradoks eksistensial. Hidup adalah kebutuhan untuk merusak. Kita makan dengan cara menghancurkan makhluk lain; kita bernapas dengan cara mengubah oksigen menjadi karbon dioksida; kita hidup dengan cara mempercepat peluruhan energi. Moralitas, jika mengikuti hukum alam, hanyalah perayaan kehancuran.
Maka satu-satunya jalan keluar adalah membalik pandangan etika. Kebaikan bukan lagi hidup sesuai dengan alam, melainkan justru melawannya.
Perlawanan ini tentu bukan berarti mengingkari hukum fisika—mustahil bagi manusia untuk meniadakan entropi. Tetapi kita dapat menunda, memperlambat, bahkan menciptakan ruang kecil bagi kebaikan di tengah arus kehancuran.
Kedokteran, misalnya, tidak bisa menghentikan kematian, tetapi ia memperpanjang kehidupan, menunda penderitaan, memberi makna pada waktu yang singkat. Gerakan ekologis yang menyerukan keberlanjutan mungkin tak akan menyelamatkan bumi dari kehancuran kosmik, tetapi ia bisa menunda kehancuran ekologis lokal, memberi ruang hidup bagi spesies lain, dan memperlambat degradasi. Bahkan tindakan kasih sayang sehari-hari—merawat yang sakit, menghibur yang berduka, mengajar yang bodoh—adalah bentuk kecil dari perlawanan terhadap semesta yang acuh tak acuh.
Kebaikan, dengan demikian, bukanlah mengikuti hukum alam, melainkan menentangnya. Ia lahir dari kesadaran bahwa alam semesta tidak peduli pada kita, dan justru karena itulah kita memilih untuk peduli.
Makna dalam Absurditas
Albert Camus pernah mengatakan bahwa absurditas adalah benturan antara kerinduan manusia akan makna dan keheningan semesta. Dalam konteks termodinamika, absurditas itu bahkan lebih radikal: kita tidak hanya menghadapi semesta yang diam, tetapi semesta yang secara aktif bergerak menuju kehancuran.
Namun di tengah absurditas itulah manusia menemukan kebebasan. Kita tidak lagi mencari pembenaran kosmik, tidak lagi bersembunyi di balik ilusi bahwa alam adalah baik. Kita menerima kenyataan bahwa realitas adalah antagonis, dan justru dari penerimaan itulah lahir etika baru: etika melawan.
Apakah kita berutang budi pada semesta yang memberi kita kehidupan, meskipun kehidupan itu sendiri adalah jalan menuju kematian? Ataukah kita justru harus membalas dendam, dengan menciptakan kebaikan kecil sebagai bentuk penolakan terhadap rancangan jahatnya?
Mungkin jawabannya ada di antara keduanya. Hidup adalah paradoks: kita lahir dari mesin kehancuran, tetapi kita bisa memilih untuk tidak sepenuhnya tunduk padanya. Kita bisa membentuk ruang-ruang kebaikan, meski rapuh dan sementara. Kita bisa merawat, meski tahu semua akan musnah. Kita bisa mencintai, meski sadar bahwa cinta itu sendiri berada di ambang entropi.
Pada akhirnya, melawan hukum alam bukan berarti kita akan menang. Kita pasti kalah. Tetapi justru dalam kekalahan yang pasti itulah, kebaikan menemukan makna sejatinya: sebagai perlawanan yang tidak tunduk, meski pada akhirnya ditelan oleh kegelapan kosmologis.
AN