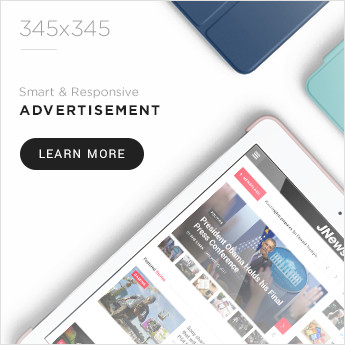Teras Merdeka – Baru-baru ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendapat gelombang protes dari sejumlah pihak terkait pembatasan jumlah calon legislatif (caleg) perempuan untuk Pemilu 2024, Kamis (11/5/2023).
Sebelumnya, jatah kursi perempuan sebagai caleg ditetapkan sebanyak 30 persen. Penetapan ini sudah ada sejak masa Reformasi yang termaktub dalam undang-undang Pasal 8 ayat (2) tentang aturan teknis penghitungan dari Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023.
Dalam peraturan tersebut, memberlakukan pembulatan ke bawah apabila perhitungan 30 persen keterwakilan perempuan dari total bakal caleg yang dibutuhkan, dan menghasilkan angka desimal kurang dari koma lima.
Sebagai contoh, apabila di suatu daerah pemilihan dibutuhkan delapan bakal caleg, maka 30 persen keterwakilan perempuan semestinya adalah 2,4 orang.
Namun karena angka desimalnya kurang dari koma lima, maka di dapil tersebut hanya ada dua bakal caleg perempuan yang memenuhi syarat.
Peraturan ini berbeda dengan peraturan KPU sebelumnya. Di mana diberlakukan pembulatan ke atas, sehingga dalam kasus tadi, keterwakilan perempuan semestinya bisa menjadi minimal tiga orang.
Hal tersebut juga mendapat atensi dari mantan komisioner KPU, Ida Budhiati dalam konferensi persnya di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat. Menurutnya, penghitungan tersebut menjadi bentuk pelanggaran terhadap hak polirik perempuan.
“Kalau pembulatan ke bawah, yang terjadi adalah pelanggaran terhadap hak politik perempuan. Undang-Undang kan menyebutnya ‘paling sedikit’ 30 persen, kalau lebih ya lebih bagus. Ini berdampak pada hilangnya hak politik perempuan,” ungkpanya, dikutip dari bbc.com, Kamis (11/6/2023).
Oleh karena banyak pihak yang memprotes hal tersebut, KPU akhirnya akan mengubah peraturan yang ada. Diketahui, dalam waktu dekat, KPU akan mengubah Pasal 8 ayat (2) tentang aturan teknis penghitungan dari Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023
Di mana yang semula penghitungannya dibulatkan ke bawah, akan diubah menjadi pembulatan ke atas.
Partisipasi Perempuan dalam Pemilu dari Tahun ke Tahun
Menurut catatan Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, aspirasi jumlah kursi perempuan sebanyak 30 persen di lembaga legislatf, muncul setelah hasil Pemilu 1999. Saat itu, menjadi momen pemilu demokratis pertama di Indonesia usai Reformasi. Di mana perempuan hanya berhasil menduduki 9 persen kursi di DPR.
Padahal pada pemilu-pemilu sebelumnya di era Orde Baru, jumlah perempuan di lembaga itu tidak pernah kurang dari dua digit.
Afirmasi tersebut, untuk pertama kalinya diteguhkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, yang mewajibkan kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam susunan daftar calon anggota legislatif.
Adapun persentase keterwakilan caleg perempuan pun terus meningkat sejak saat itu. Di antaranya yaitu 29 persen pada 2004, 33,6 persen pada 2009, 37,6 persen pada 2014, dan 40 persen pada 2019.
Meskipun begitu, jumlah caleg perempuan yang berhasil menduduki kursi di parlemen belum pernah mencapai 30 persen.
Pada 2004, jumlahnya hanya 11,8 persen, lalu 18 persen pada 2009, 17 persen pada 2014, dan 20 persen pada 2019. Padahal, jumlah pemilih perempuan sejak Pemilu 2004 tidak pernah kurang dari 49 persen.
Pentingnya Keterwakilan Perempuan dalam Merumuskan Kebijakan
Sejumlah politisi, khususnya politisi perempuan menilai berkurangnya jaminan soal keterwakilan perempuan dapat menghambat upaya untuk mengarusutamakan perspektif gender dalam berbagai kebijakan.
Misalnya saja terkait disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pembahasan Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga, serta Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak.
Di mana pengesahan UU tersebut sudah pasti tak lepas dari keberadaan para perempuan yang duduk di kursi strategis dalam pengambilan kebijakan.
Namun, keberadaan perempuan tidak hanya mengambil persperktif dalam isu terkait perempuan saja, tetapi juga dibutuhkan dalam isu-isu lainnya.
Keberadaan perempuan menjadi penting dalam pengambilan kebijakan terutama karena perempuan dinilai bisa melihat permasalahannya lebih detil. Terutama karena perempuan berhubungan langsung dengan level mikro.
Namun dalam kenyataannya, sejumlah politisi juga menganggap bahwa keberadaan perempuan di parlemen yang masih belum dianggap sebagai subjek. Terlebih, dalam politik, seringkali diwibawakan sebagai di area maskulin.
Akan tetapi, bukan tidak mungkin jika pandangan tersebut akan berubah seiring waktu serta pembaharuan yang lebih baik dalam proses pengambilan kebijakan.